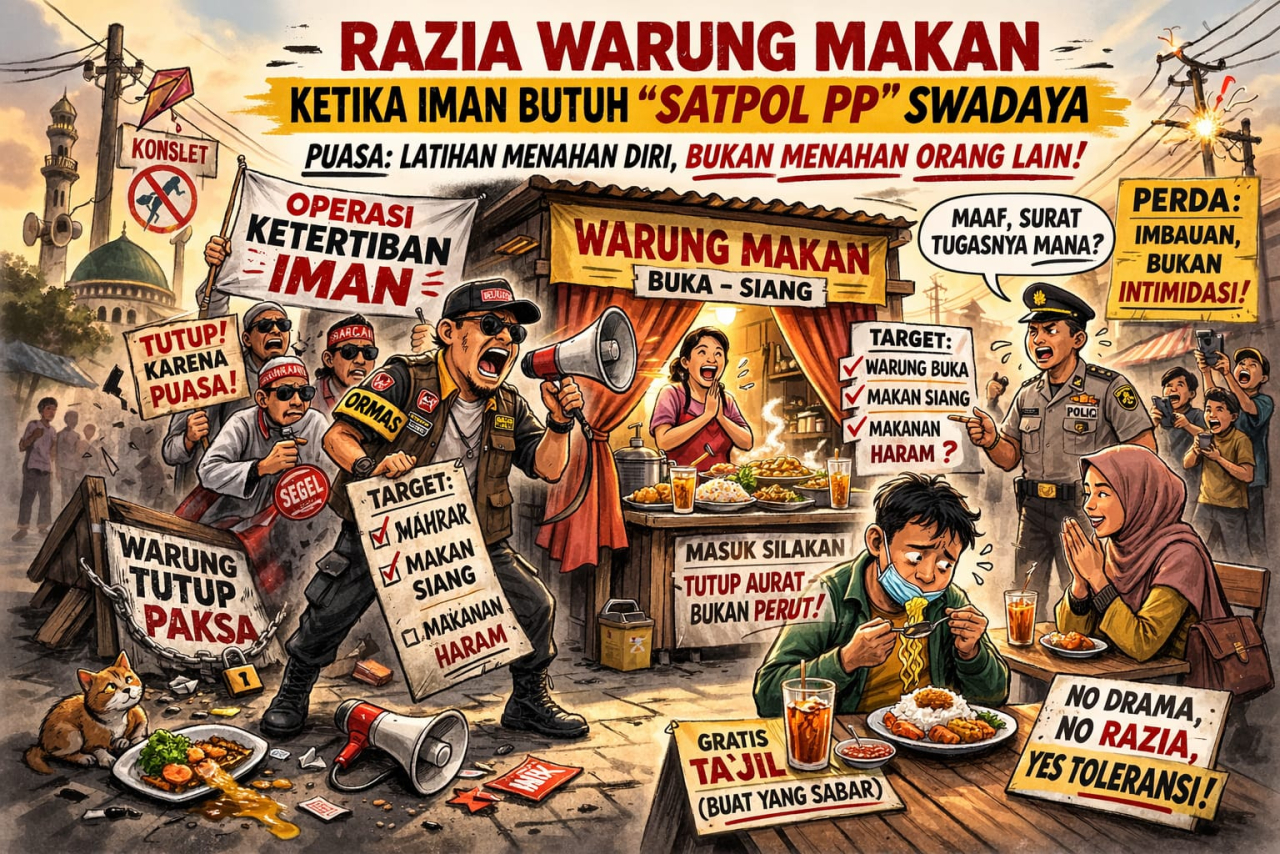Ketika Garda Terdepan Berubah Menjadi Ancaman: Menelusuri Akar Masalah Keamanan

*Oleh: Ken Bimo Sultoni
Lini jagat maya saat ini dihiasi oleh pemberitaan terkait tindak pidana kekerasan dan pembunuhan terhadap seorang warga Aceh bernama imam masykur yang dilakukan oleh anggota TNI dari kesatuan pasukan pengamanan presiden atau Paspampres.
Diketahui bahwa imam masykur diculik dari tempat usahanya oleh pelaku yang berinisial RM dengan beberapa temannya yang juga berlatar bekang tentara pada tanggal 14 Agustus 2023.
Hingga pada akhirnya jasad korban ditemukan di sungai karawang setelah sebelumnya di buang ke waduk didaerah Purwakarta.
Hal ini pastinya menjadi sebuah berita miris serta ironis yang mana seharusnya seorang aparat militer bertugas untuk membela serta mengabdi pada bangsanya berubah menjadi layaknya mesin pembunuh bangsanya sendiri dengan dalih ekonomi.
Situasi ini pun makin menguatkan dugaan bahwa institusi pertahanan dan keamanan Indonesia sedang tidak dalam kondisi baik baik saja. Sebelumnya Indonesia dihebohkan dengan kasus Sambo, pembunuhan seorang polisi yang ternyata diklakukan oleh atasannya sendiri.
Pelaku yang notabene merupakan seorang perwira tega melakukan tindakan pembunuhan terhadap bawahannya tersebut dengan dalih menjaga kehormatan.
Hal ini menambah rentetan panjang kasus pelanggaran dan pencorengan nama baik institusi pertahanan dan keamanan Indonesia.
Problem Mengakar dan Turunan
Perlu dilakukan suatu bentuk tinjauan yang mendalam terkait situasi yang terjadi, khususnya berkaitan dengan kondisi psikologis dan juga kebutuhan para personil militer dan kepolisian.
Aspek psikologis menjadi sangat penting. Anggota militer dan kepolisian sering kali menghadapi tekanan dan stres yang besar dalam pekerjaan mereka.
Ketersediaan layanan dukungan mental dan kesejahteraan harus ditingkatkan, termasuk akses mudah ke layanan konseling dan bantuan bagi mereka yang mengalami masalah psikologis. Layaknya dalam film naga bonar, ketidakpatuhan dan juga ketidakdisplinan personil militer dan juga kepolisian paling mungkin disebabkan oleh adanya situasi kacau baik yang disebabkan dalam tubuh institusi itu maupun dipengaruhi oleh lingkungannya.
Teringat dikala naga bonar dan juga kelompoknya yang saat itu tergabung dalam laskar laskar rakyat berani menamai dan memberi jabatan terhadap dirinya sendiri serta bergerak tanpa alur komando dari pimpinannya.
Meski berupa film akan tetapi hal ini benar benar terjadi di dunia nyata, Pada tahun 1948 Mohammad Hatta yang kala itu menjabat sebagai perdana menteri mengusulkan kebijakan Rekonstruksi dan Rasionalisasi Angkatan Perang (RERA) untuk menertibkan laskar laskar rakyat dan juga kelompok paramiliter yang dimiliki Indonesia pasca kemerdekaan untuk didisiplinkan dan dibenahi admintrasi dan pendataan kepangkatannya.
Kala itu angkatan perang Indonesia tersebar dalam bentuk laskar, tentara resmi hingga paramiliter seperti tentara pelajar sehingga menjadi ancaman serius bagi alur komando militer Indonesia yang tengah menghadapi agresi militer belanda.
Tidak dapat disangkal bahwa nilai etika dan moral sangat penting dalam membentuk karakter anggota militer. Kekerasan dan pelanggaran yang melibatkan anggota militer dan kepolisian dapat mengancam stabilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan keamanan.
Dalam hal ini, dukungan psikologis dan kesehatan mental bagi para prajurit menjadi faktor esensial yang tidak boleh diabaikan. Institusi pertahanan dan keamanan perlu menyediakan layanan yang memadai untuk membantu anggota yang mungkin mengalami tekanan psikologis akibat tugas-tugas berat yang diemban.
Problematika seperti pertimbangan psikologis, kesejahteraan anggota serta pemahaman akan disiplin administratif seringkali menjadi permasalahan yang tak kunjung usai.
Pola-pola yang sama dan berulang seperti adanya pelanggaran bahkan tindakan yang lebih ekstrem mungkin saja terjadi apabila masalah tersebut tetap dibiarkan.
Selain itu masih rendahnya pemahaman para personel militer dan kepolisian terhadap nilai nilai demokrasi dan juga kemanusiaan juga menjadi beban utama yang terus terjadi pada lintas generasi institusi ini untuk mengubah wajah.
Di dunia yang serba cepat dan transparan saat ini semua bidang kehidupan termasuk elemen kemiliteran dan kepolisian dipaksa untuk harus tunduk pada nilai nilai demokrasi.
Oleh karenanya penting untuk bisa menanamkan pemahaman kepada seluruh personil militer maupun kepolisian tentang pendekatan human security dalam setiap operasi yang dilakukan.
Reformasi Sistem Pendidikan Militer dan Kepolisian
Tinjauan mendalam perlu dilakukan untuk memahami akar masalah dan mengidentifikasi solusi yang tepat. Salah satu aspek yang perlu ditinjau adalah pembaharuan sistem seleksi, pelatihan, dan pendidikan yang diberikan kepada anggota militer dan kepolisian.
Proses seleksi harus sangat ketat untuk memastikan hanya individu yang memiliki integritas, etika, dan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tanggung jawabnya yang dapat diterima.
Pelatihan dan pendidikan harus mencakup aspek hukum, hak asasi manusia, etika, kepemimpinan, dan penanganan situasi yang kompleks.
Pendidikan tentang hak asasi manusia, etika, dan nilai-nilai demokrasi juga harus ditanamkan dengan kuat dalam pelatihan anggota militer dan kepolisian.
Ini akan membantu mengubah budaya organisasi menjadi lebih berfokus pada pelayanan kepada masyarakat dan penghormatan terhadap hak-hak individu. Penting untuk melibatkan masyarakat dan organisasi non-pemerintah dalam proses perbaikan institusi pertahanan dan keamanan. Transparansi dan partisipasi publik dapat membantu membangun kepercayaan dan memastikan akuntabilitas institusi tersebut.
Menurut Peneliti pendidikan Militer, Anders Mcdonald Sookermany mengungkapkan bahwa pendidikan militer tradisional seringkali bersifat universal, struktur dan objektif yang bertujuan untuk memupuk rasa identitas bersama.
Dampak pendidikan yang diinginkan ialah mendorong lingkungan pembelajaran yang seragam dan meningkatkan kemampuan sesuai dengan skenario yang dipelajari dan dipraktekan dalam operasi militer maupun keamanan.
Menurutnya seharusnya ada alternatif lain yang bisa digunakan untuk menghadapi era posmodernisme yang sedang terjadi salah satunya dengan cara merangkul nilai nilai keberagaman dibandingkan keseragaman.
Dunia posmodernis akan mengahadapi nilai nilai seperti konstruktivisme, kompleksitas dan kontekstualisme.
Situasi yang tengah melanda Indonesia, sebagaimana diilustrasikan dalam tulisan ini, sungguh membutuhkan perhatian mendalam dari semua lapisan masyarakat.
Berita mengenai tindak pidana kekerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anggota TNI terhadap seorang warga sipil telah mengguncang pondasi institusi pertahanan dan keamanan negara.
Pemberitaan ini menyiratkan suatu ironi yang memilukan; aparat yang seharusnya bertugas menjaga dan melindungi keselamatan rakyat, justru terlibat dalam peristiwa keji yang merusak citra dan martabat bangsa.
Rentetan peristiwa semacam ini mengekspos kelemahan dalam sistem pendidikan, disiplin, serta pengawasan yang seharusnya mengendalikan perilaku para anggota institusi ini.
Dalam menghadapi kenyataan pahit ini, kita perlu mengambil langkah-langkah tegas untuk mereformasi pendidikan dan pelatihan militer, memperbaiki sistem pengawasan yang sudah lapuk, dan membangun mekanisme transparansi serta pertanggungjawaban yang kuat.
Problem Pengawasan
Lebih dari sekadar reformasi internal, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian institusi ini menjadi semakin penting. Masyarakat berperan dalam memastikan bahwa nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan profesionalisme tetap dijaga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh aparat pertahanan dan keamanan.
Langkah ini juga dapat menjadi jalan untuk mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak-hak warga. Pengawasan yang dilakukan pun harus bersifat demokratis yaitu dengan cara mensyaratkan keterlibatan elemen demokratis yang terdiri dari dua jenis yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh eksekutif, legislatif dan yudikatif sebagai aktor negara, serta pengawasan eksternal yang berasal dari masyarakat.
Selain itu, Mekanisme pelaporan yang aman dan anonim juga harus disediakan bagi anggota militer dan kepolisian yang ingin melaporkan perilaku tidak etis atau pelanggaran yang mereka saksikan.
Lebih lanjut pengamatan politik keamanan Muhammad Haripin juga menilai bahwa setidaknya ada lima faktor lain yang menjadi probelamtika pengawasan demokratis (Democratic Oversight) terhadap sektor keamanan. Pertama ialah terjadinya konflik kepentingan diantara elite polik dan keamanan yang mengaburkan antara profesionalisme dan politik partisan.
Kedua, minimnya kapasitas pengetahuan dari anggota legislatif dan aktor pengawas untuk bisa memahami teknis pengawasan tersebut memperburuk implementasi dari pengawasan demokratis.
Ketiga, terjadinya pembungkaman suara demokratis terhadap praktik pengawasan di parlemen yang diakibatkan oleh tekanan politik dan ancaman recall kepada anggota partai yang berani berbeda pendapat terutama pada pihak-pihak yang tergabung dalam koalisi pemerintah berkuasa.
Keempat, Praktik pengawasan tak jarang menemui tantangan dari aktor keamanan negara itu sendiri. Dengan dalih kerahasian seringkali membuat proses investigasi lebih mendalam atas dugaan pelanggaran hukum menjadi terhambat dan akses informasi yang disediakan pun amat terbatas dengan alasan tersebut.
Kelima, terjadi perbedaan pendapat dan kepentingan antara aktor pengawas dalam menilai suatu aktivitas aktor keamanan. Contohnya keterlibatan tentara atau personil kepolisian pada aktivitas publik seperti penanganan Covid dengan alasan urgensifitas dipandang sesuatu yang lumrah serta wajib dilakukan, sementara disisi lain kalangan sipil menilai bahwa hal tersebut haruslah terlebih dahulu dituangkan dalam keputusan politik negara.
Perbedaan pendapat inilah yang pada akhirnya jika tidak menemui titik temu pada akhirnya mengarah pada hubungan konflik. Untuk kembali membangun institusi pertahanan dan keamanan yang dapat dipercaya oleh masyarakat, diperlukan komitmen serius dari pemerintah, pemimpin militer, serta partisipasi aktif dari seluruh warga negara.
Reformasi tidaklah mudah dan memerlukan waktu, namun dengan kesungguhan dalam memperbaiki struktur dan budaya organisasi, kita dapat berharap bahwa masa depan pertahanan dan keamanan Indonesia akan lebih cerah, lebih profesional, dan lebih sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan.
*Pengamat Politik Keamanan, Alumni S2 Sekolah Kajian Strategik dan Global Universitas Indonesia dan Mahasiswa Doktoral Ilmu Sosial Universitas Diponegoro
Editor : Ibrahim